1 x 7 ( bagian 2)
Kemarin, lima tahun yang lalu..
Pagi itu Mas Adhi, sepupu kami datang ke rumah. Mencoba memberikan dukungan moril untuk saya dan Woro. Kami berdua sempat berbincang sambil sarapan di meja makan.
"Kamu ingat ga, ustadz yang pernah aku bawa ke sini?" tanyanya.
Saya hanya mengangguk. Tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini.
"Tadi mas cerita soal keadaan Bapak," sambungnya. "Ustadz bilang, kalau saat ini masih ada ganjalan dari orang lain yang menghalangi dia."
Saya terdiam.
"Coba kamu inget lagi deh, kira-kira ada ga yang belum kamu ikhlasin?"
22 Juni 2012 pukul 18.00
Malam ini adalah malam ulang tahun Jakarta. Banyak mall di Jakarta menawarkan diskon berbelanja. Rekan-rekan kerja mengajak saya untuk mengunjungi Pejaten Village setelah waktu kerja, hanya sekedar melihat apakah ada barang yang bisa dimiliki. Saya pun mengiyakan, sekedar melepas penat dan kesedihan.
Bapak sakit. Sudah lebih dari satu bulan. Tiga minggu saya habiskan menemaninya di rumah sakit. Penyakit lever yang sudah dideritanya sekian lama, kambuh. Entah apa sebabnya. Padahal sejak mama meninggal dua tahun yang lalu, Bapak sudah tidak pernah bekerja. Harinya dihabiskan di rumah menonton televisi, tidur, atau sekedar bermain dengan Aqila, keponakan kami yang sering dititipkan di rumah.
Dua kali jantung saya mencelos. Bapak hilang kesadaran di rumah sakit karena gula darahnya yang menurun drastis. Setiap hari saya mengukur lingkar perut Bapak yang terlihat membesar. Berharap saya melihat angkanya turun. Di minggu kedua di rumah sakit, Bapak minta pulang dengan memaksa untuk di rawat di rumah. Saya pun menyetujuinya. Menjaga Bapak di rumah sakit cukup menyiksa batin saya. Pengalaman menjaga Mama di rumah sakit yang sama, sedikit membuat saya trauma.
Seminggu di rumah, kami membawa Bapak ke sebuah klinik obat alternatif yang direkomendasikan bulik saya. Awalnya dia menolak. "Sudahlah," katanya. Tapi tidak ada yang menggubrisnya. Gak boleh, Bapak harus sembuh. Hingga akhirnya dia manut. Walau saya tahu, semuanya itu untuk menyenangkan keluarganya.
"Pulang mas," jawab Mbak Iyah malam itu, begitu saya telepon minta izin untuk pulang telat karena akan window shopping dulu.
"Bapak gimana, mbak?" tanya saya mulai curiga.
"Kamu lihat aja sendiri,"
Jawaban Mbak Iyah langsung memberikan tanda ada sesuatu yang gak beres di rumah. Saya pun membatalkan rencana dan langsung segera pulang. Saat saya tiba, raut muka Mbak Iyah makin membuat jantung saya berdebar.
"Bapak ga mau minum obat," lapornya begitu saya selesai memasukkan mobil ke garasi. Di kamar Woro, tempat tidur favoritnya, saya melihat Bapak sudah gelisah. Pandangannya kacau. Tangannya memegang erat teralis jendela.
"Pak. Minum obatnya ya." pinta saya.
Bapak tidak menanggapi. "Bu, tunggu kulo, Bu," tiba-tiba dia meraung. Seketika itu pula air mata saya mengalir. Bapak memanggil ibunya, nenek saya yang sudah lama tiada. Persis. Sama persis dengan yang dilakukan Mama beberapa waktu sebelum ia meninggal.
Hal-hal berikutnya menjadi kejadian yang tidak bisa saya lupa. Berdua dengan Mbak Iyah, kami mengangkat Bapak ke kamarnya sendiri supaya ia bisa tidur dengan lebih luas. Kami panggil pak Haji (tetangga terdekat kami). Kami panggil keluarga besar kami. Bahkan Woro yang sedang shift malam pun, saya minta pulang. Bapak sudah tidak sadarkan diri. Matanya terbuka tapi tak merespon. Hanya mulutnya yang masih bergerak-gerak menandakan memang dia masih "ada".
Sebagai seorang programmer. Bapak itu ibarat aplikasi yang punya bug. Dan saya berusaha untuk memperbaikinya. Di malam itu, hati kecil saya ingin membawanya ke rumah sakit. Mengupayakan semaksimal mungkin yang kita bisa. Tapi hampir semua orang tidak berpendapat yang sama. Pak Haji, bahkan om dan bulik saya. Saat ini Bapak sudah kritis dan tidak ada gunanya lagi untuk membawa ke rumah sakit. Hati saya (dan mungkin) Woro hancur berkeping-keping. Kami lewati hari itu dengan orang tua satu-satunya yang masih kami miliki, yang sedang berjuang dengan sakaratul mautnya.
Pagi itu, usai sarapan dengan Mas Adhi, saya dan Woro menghampiri Bapak kembali. Di luar, mobil Ambulance sudah datang. Setidaknya Allah sudah melihat bahwa si programmer ini masih berusaha. Bapak menatap saya. Atau setidaknya saya merasa ia menatap saya. Memori saya terbang ke pelajaran 1 x 7, dua puluh tahun sebelumnya.
Saya usap dahinya, saya ciumi pipinya. Saya dekatkan mulut saya ke telinga kanannya.
"Pak, saya ikhlas. Kalau Bapak mau pergi," bisik saya. Untuk pertama kalinya saya ingin Bapak mati saja. Rasanya kejam sekali. Air mata saya langsung pecah. Saya merasa kalah dengan ujian yang Tuhan kasih ke saya. Saya merasa bersalah sama Bapak. Sesenggukan saya bisikan kalimat Tuhan, hingga ia hembuskan nafas terakhirnya.
Allahummaghfir lii wa liwaalidayya warhamhuma kamaa rabbayanii shaghiraa
Pagi itu Mas Adhi, sepupu kami datang ke rumah. Mencoba memberikan dukungan moril untuk saya dan Woro. Kami berdua sempat berbincang sambil sarapan di meja makan.
"Kamu ingat ga, ustadz yang pernah aku bawa ke sini?" tanyanya.
Saya hanya mengangguk. Tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini.
"Tadi mas cerita soal keadaan Bapak," sambungnya. "Ustadz bilang, kalau saat ini masih ada ganjalan dari orang lain yang menghalangi dia."
Saya terdiam.
"Coba kamu inget lagi deh, kira-kira ada ga yang belum kamu ikhlasin?"
22 Juni 2012 pukul 18.00
Malam ini adalah malam ulang tahun Jakarta. Banyak mall di Jakarta menawarkan diskon berbelanja. Rekan-rekan kerja mengajak saya untuk mengunjungi Pejaten Village setelah waktu kerja, hanya sekedar melihat apakah ada barang yang bisa dimiliki. Saya pun mengiyakan, sekedar melepas penat dan kesedihan.
Bapak sakit. Sudah lebih dari satu bulan. Tiga minggu saya habiskan menemaninya di rumah sakit. Penyakit lever yang sudah dideritanya sekian lama, kambuh. Entah apa sebabnya. Padahal sejak mama meninggal dua tahun yang lalu, Bapak sudah tidak pernah bekerja. Harinya dihabiskan di rumah menonton televisi, tidur, atau sekedar bermain dengan Aqila, keponakan kami yang sering dititipkan di rumah.
Dua kali jantung saya mencelos. Bapak hilang kesadaran di rumah sakit karena gula darahnya yang menurun drastis. Setiap hari saya mengukur lingkar perut Bapak yang terlihat membesar. Berharap saya melihat angkanya turun. Di minggu kedua di rumah sakit, Bapak minta pulang dengan memaksa untuk di rawat di rumah. Saya pun menyetujuinya. Menjaga Bapak di rumah sakit cukup menyiksa batin saya. Pengalaman menjaga Mama di rumah sakit yang sama, sedikit membuat saya trauma.
Seminggu di rumah, kami membawa Bapak ke sebuah klinik obat alternatif yang direkomendasikan bulik saya. Awalnya dia menolak. "Sudahlah," katanya. Tapi tidak ada yang menggubrisnya. Gak boleh, Bapak harus sembuh. Hingga akhirnya dia manut. Walau saya tahu, semuanya itu untuk menyenangkan keluarganya.
"Pulang mas," jawab Mbak Iyah malam itu, begitu saya telepon minta izin untuk pulang telat karena akan window shopping dulu.
"Bapak gimana, mbak?" tanya saya mulai curiga.
"Kamu lihat aja sendiri,"
Jawaban Mbak Iyah langsung memberikan tanda ada sesuatu yang gak beres di rumah. Saya pun membatalkan rencana dan langsung segera pulang. Saat saya tiba, raut muka Mbak Iyah makin membuat jantung saya berdebar.
"Bapak ga mau minum obat," lapornya begitu saya selesai memasukkan mobil ke garasi. Di kamar Woro, tempat tidur favoritnya, saya melihat Bapak sudah gelisah. Pandangannya kacau. Tangannya memegang erat teralis jendela.
"Pak. Minum obatnya ya." pinta saya.
Bapak tidak menanggapi. "Bu, tunggu kulo, Bu," tiba-tiba dia meraung. Seketika itu pula air mata saya mengalir. Bapak memanggil ibunya, nenek saya yang sudah lama tiada. Persis. Sama persis dengan yang dilakukan Mama beberapa waktu sebelum ia meninggal.
Hal-hal berikutnya menjadi kejadian yang tidak bisa saya lupa. Berdua dengan Mbak Iyah, kami mengangkat Bapak ke kamarnya sendiri supaya ia bisa tidur dengan lebih luas. Kami panggil pak Haji (tetangga terdekat kami). Kami panggil keluarga besar kami. Bahkan Woro yang sedang shift malam pun, saya minta pulang. Bapak sudah tidak sadarkan diri. Matanya terbuka tapi tak merespon. Hanya mulutnya yang masih bergerak-gerak menandakan memang dia masih "ada".
Sebagai seorang programmer. Bapak itu ibarat aplikasi yang punya bug. Dan saya berusaha untuk memperbaikinya. Di malam itu, hati kecil saya ingin membawanya ke rumah sakit. Mengupayakan semaksimal mungkin yang kita bisa. Tapi hampir semua orang tidak berpendapat yang sama. Pak Haji, bahkan om dan bulik saya. Saat ini Bapak sudah kritis dan tidak ada gunanya lagi untuk membawa ke rumah sakit. Hati saya (dan mungkin) Woro hancur berkeping-keping. Kami lewati hari itu dengan orang tua satu-satunya yang masih kami miliki, yang sedang berjuang dengan sakaratul mautnya.
Pagi itu, usai sarapan dengan Mas Adhi, saya dan Woro menghampiri Bapak kembali. Di luar, mobil Ambulance sudah datang. Setidaknya Allah sudah melihat bahwa si programmer ini masih berusaha. Bapak menatap saya. Atau setidaknya saya merasa ia menatap saya. Memori saya terbang ke pelajaran 1 x 7, dua puluh tahun sebelumnya.
Saya usap dahinya, saya ciumi pipinya. Saya dekatkan mulut saya ke telinga kanannya.
"Pak, saya ikhlas. Kalau Bapak mau pergi," bisik saya. Untuk pertama kalinya saya ingin Bapak mati saja. Rasanya kejam sekali. Air mata saya langsung pecah. Saya merasa kalah dengan ujian yang Tuhan kasih ke saya. Saya merasa bersalah sama Bapak. Sesenggukan saya bisikan kalimat Tuhan, hingga ia hembuskan nafas terakhirnya.
Would you tell me I was wrong?
Would you help me understand?
Are you looking down upon me?
Are you proud of who I am?
There's nothing I wouldn't do
To have just one more chance
To look into your eyes and see you looking back
Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do
And I've hurt myself, oh, oh, oh.
If I had just one more day
I would tell you how much that I've missed you since you've been away
Allahummaghfir lii wa liwaalidayya warhamhuma kamaa rabbayanii shaghiraa
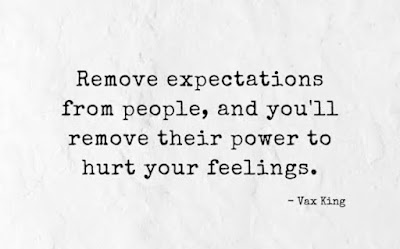
Comments